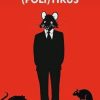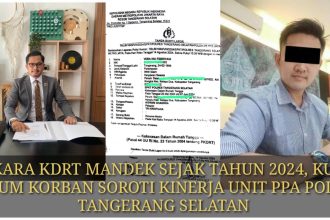Oleh : Bahrulhadi Nursyamsu
Di tengah padatnya beton dan narasi kekuasaan, ruang publik sering kali terasa menyempit. Tapi bagi masyarakat sipil, ruang bukan sekadar tempat—ia adalah makna, simbol, dan alat perjuangan.
Ambil contoh Piknik Melawan, sebuah aksi yang dilakukan di pelataran gedung DPR RI. Bukan orasi, bukan teriakan—melainkan piknik. Aksi ini adalah bentuk perlawanan kreatif yang mencoba merebut kembali gedung DPR sebagai ruang rakyat. Sebuah pengingat bahwa gedung itu bukan milik elite, tapi milik warga negara.
Ruang publik, secara sederhana, adalah ruang di mana warga bisa hadir, berdiskusi, dan menyampaikan suara. Tapi konsep ini punya sejarah intelektual yang panjang. Jürgen Habermas, filsuf asal Jerman, menyebut ruang publik sebagai arena rasional, di mana warga bebas bertukar gagasan dan mengawasi kekuasaan. Ruang publik adalah jantung demokrasi.
Namun dalam praktiknya, ruang publik tak selalu tersedia. Ia kerap dikebiri oleh komersialisasi, dibatasi oleh regulasi, atau dipagari oleh kekuasaan. Di sinilah pentingnya aksi okupasi ruang.
Okupasi ruang berarti mengambil alih ruang secara kolektif—baik yang publik maupun privat—untuk menandai eksistensi, menyampaikan aspirasi, dan menantang dominasi. Dalam kajian gerakan sosial dan geografi kritis, ini disebut spatial practice: praktik ruang yang menggugat tatanan dominan.
Contoh yang lebih sunyi namun tak kalah kuat: Aksi Kamisan. Sejak 2007, keluarga korban pelanggaran HAM berdiri diam setiap Kamis di depan Istana Negara. Tidak teriak. Tidak ramai. Tapi keberadaan mereka menyuarakan luka, harapan, dan penolakan terhadap lupa. Mereka merebut ruang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan tubuh dan keberanian untuk hadir. Ruang depan istana, simbol kekuasaan, dijadikan panggung sunyi untuk ingatan dan keadilan.
Gagasan ini mengakar dari pemikiran Henri Lefebvre. Baginya, ruang kota bukan netral. Ia diciptakan dan dikuasai oleh relasi ekonomi dan politik. Karena itu, warga berhak untuk merebutnya kembali—sebuah gagasan yang ia sebut right to the city. David Harvey, yang mengembangkan ide ini, menyebut aksi warga di ruang kota sebagai bentuk perjuangan kelas modern terhadap kapitalisme neoliberal.
Dalam konteks Indonesia, ruang publik idealnya adalah fondasi dari partisipasi warga. Namun ketika ruang fisik dibatasi, atau ketika suara warga dibungkam, maka aksi-aksi seperti Piknik Melawan dan Aksi Kamisan menjadi bentuk perlawanan yang sah dan penting. Mereka adalah cara warga mengatakan: “Kami ada. Kami berhak. Kami tak akan diam.”
Di era ketika demokrasi kerap diklaim tapi jarang diwujudkan, praktik okupasi ruang menjadi napas baru bagi partisipasi warga. Ruang publik tak bisa hanya jadi wacana di atas kertas. Ia harus hidup—dihirup, dipijak, dan diperjuangkan bersama.
( Red )