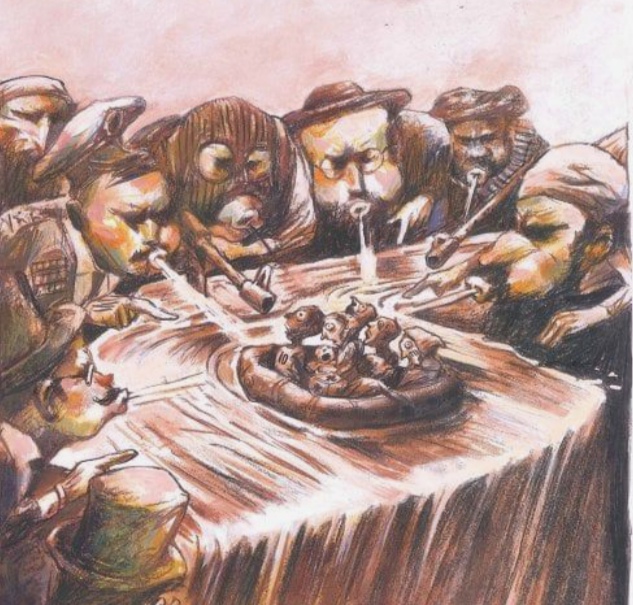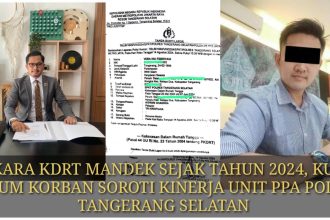Oleh : Cecep Anang Hardian
Gagasan Trias Politica pertama kali dicetuskan oleh filsuf dan pemikir politik asal Prancis, Montesquieu, dalam karya monumentalnya De L’Esprit des Lois (1748). Dalam karya tersebut, Montesquieu menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Inggris, dan merumuskan bahwa untuk mencegah kekuasaan yang tiranik, kekuasaan dalam negara harus dibagi menjadi tiga fungsi utama:
Legislatif (membuat undang-undang)
Eksekutif (menjalankan undang-undang)
Yudikatif (menafsirkan dan menegakkan hukum)
Tujuannya bukan hanya untuk membagi kekuasaan, melainkan untuk menciptakan sistem checks and balances di mana masing-masing kekuasaan bisa saling mengawasi dan menyeimbangkan. Prinsip ini kemudian menjadi landasan penting bagi perkembangan negara demokrasi modern.
Implementasi Trias Politica dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Indonesia secara konstitusional menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 pascareformasi, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi:
Kekuasaan Legislatif: DPR dan DPD yang membentuk undang-undang.
Kekuasaan Eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kementerian.
Kekuasaan Yudikatif: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawal keadilan.
Namun, dalam praktiknya, pemisahan ini tidak berjalan murni dan sering kali dikaburkan oleh faktor politik praktis, transaksi kekuasaan, dan dominasi elit politik.
Ketidakefektifan Trias Politica di Era Indonesia Kontemporer. Lemahnya Fungsi Pengawasan Legislatif
DPR seharusnya menjadi lembaga yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun kenyataannya, banyak kebijakan pemerintah yang disahkan tanpa perdebatan publik yang memadai. Misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja, KUHP baru, dan revisi UU KPK semua dilakukan secara cepat dan minim partisipasi publik.
Mayoritas anggota DPR berasal dari partai-partai pendukung pemerintah, yang membuat lembaga ini lebih mirip perpanjangan tangan eksekutif daripada sebagai pengawas kekuasaan. Oposisi menjadi lemah atau bahkan nyaris simbolik.
Intervensi terhadap Kekuasaan Kehakiman Salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah yudikatif Indonesia adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang memungkinkan seseorang yang belum cukup umur secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Putusan ini memicu kritik luas karena dinilai tidak independen dan terlalu politis, khususnya karena berkaitan dengan putra presiden saat itu. Kecurigaan terhadap pengaruh politik dalam dunia peradilan juga diperkuat oleh lemahnya integritas beberapa hakim, korupsi di lembaga kehakiman, serta tumpulnya peradilan dalam menghadapi pelanggaran oleh elit politik dan ekonomi.
Kooptasi Partai Politik oleh Oligarki
Sistem kepartaian di Indonesia telah berkembang menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan elit. Partai-partai besar cenderung tidak memiliki ideologi yang kuat dan lebih mengutamakan akomodasi kepentingan pribadi dan bisnis.
Ketika partai sudah tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat, maka mereka juga tidak akan menjalankan fungsi kontrol dan keseimbangan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Dalam kondisi ini, Trias Politica tidak bisa berjalan karena seluruh cabang kekuasaan sebenarnya telah dikendalikan oleh jejaring kekuasaan yang sama.
Dominasi Kekuasaan Eksekutif. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden memang memiliki kekuasaan besar, termasuk hak untuk menunjuk dan memberhentikan menteri, membuat peraturan pemerintah, serta mengontrol anggaran. Namun dalam praktik, presiden juga memiliki pengaruh besar terhadap arah legislatif dan bahkan yudikatif.
Ketika presiden memiliki pengaruh kuat terhadap MK (sebagai contoh), terhadap mayoritas parlemen (karena koalisi besar), dan terhadap aparat penegak hukum, maka tidak ada lagi kekuasaan yang benar-benar mampu mengimbanginya.
Ketika sistem Trias Politica tidak berfungsi dengan baik, sejumlah dampak buruk bisa terjadi,Pelemahan demokrasi, karena kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada satu pihak. Turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) Tumbuhnya otoritarianisme terselubung yang dibungkus dalam demokrasi prosedural.
Maraknya korupsi sistemik, karena tidak ada kekuasaan yang benar-benar mengawasi.Pemisahan kekuasaan bukan sekadar teori yang kaku, tetapi fondasi etis dan institusional bagi demokrasi yang sehat. Ketika trias politica hanya dijalankan secara simbolis, maka bangsa ini kehilangan salah satu pelindung terpenting dari penyalahgunaan kekuasaan. Perlu reformasi serius dalam,Independensi lembaga yudikatif, termasuk pemilihan hakim yang bebas dari intervensi politik.
Penguatan peran DPR, termasuk penguatan fungsi pengawasan dan keberanian bersikap kritis terhadap pemerintah. Reformasi partai politik, agar lebih berakar pada ideologi dan akuntabilitas terhadap rakyat, bukan hanya pada elite dan pemodal.
Peningkatan literasi politik masyarakat, agar rakyat bisa menjadi kontrol sosial yang aktif. Trias Politica bukanlah dogma, melainkan prinsip fundamental untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin kebebasan warga negara. Sayangnya, di Indonesia saat ini, prinsip tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika ketiga cabang kekuasaan berjalan dalam satu orbit kepentingan, maka demokrasi tidak lagi hidup yang tersisa hanyalah prosedur tanpa substansi.
( Edi/Red )