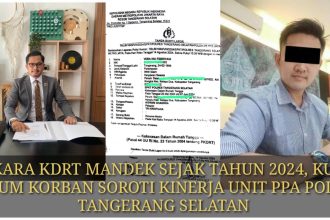Oleh : Cecep Anang Hardian
Setiap 21 April, sebagian besar dari kita tahu harus memakai apa. Kebaya. Jarik. Konde. Bahkan anak-anak laki-laki pun kadang-kadang ikut tampil dengan blangkon dan beskap, entah mengerti atau tidak mengapa semua ini dilakukan. Di sekolah, lomba puisi. Di kantor, webinar tentang perempuan. Di timeline, kutipan Kartini berseliweran—“Habis gelap terbitlah terang”—diunggah dengan caption penuh semangat.
Tapi sesudah itu? Kembali gelap. Kartini dibiarkan menjadi lambang, bukan percakapan. Dan kita lebih sibuk memperingatinya, ketimbang memahami isi surat-suratnya yang tajam, getir, dan penuh tanya.
Kartini Tidak Minta Diperingati
Kartini tidak ingin jadi patung. Ia ingin didengar. Ia tidak meminta kita memakai kebaya, tapi mengerti apa artinya jadi perempuan di negeri yang suka menaruh perempuan di pojokan. Ia tidak menuntut panggung, tapi ingin perempuan bebas bicara—tentang pendidikan, tentang tubuhnya, tentang hidupnya sendiri.
Kartini tumbuh dalam ruang yang sempit tapi pikirannya melampaui dinding-dinding itu. Di saat perempuan lain bahkan tidak boleh membaca, ia menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, tentang apa rasanya hidup sebagai perempuan Jawa dalam struktur yang kaku dan tidak masuk akal. Ia ingin sekolah untuk perempuan. Ingin perempuan berpikir. Ingin perempuan jadi manusia sepenuhnya, bukan hanya pelengkap laki-laki.
Tapi jarang kita ingat bahwa di balik Kartini yang kita kenal, ada sosok lain yang berjasa besar membuka jendela itu: kakaknya sendiri, R.M. Soekartono.
Kakak Kartini: Jenius yang Tak Pernah Dirayakan
Nama Soekartono mungkin terdengar asing, padahal ia adalah salah satu tokoh paling menakjubkan dalam sejarah Indonesia. Jauh sebelum Soekarno meneriakkan kemerdekaan, jauh sebelum Tan Malaka berbicara tentang republik dan revolusi, Soekartono sudah lebih dulu menjelajahi dunia dengan otak tajam dan tekad yang sunyi.
Ia adalah orang Hindia Belanda pertama yang belajar di luar negeri. Di masa ketika lebih dari 90 persen rakyat Indonesia bahkan belum bisa membaca dan menulis, Soekartono sudah kuliah di Belanda, fasih berbahasa Eropa, dan menjadi penerjemah diplomatik antara dua negara yang sedang bertikai.
Satu waktu, para pejabat Eropa panik mencarinya. Mereka butuh jasa intelektualnya dalam negosiasi penting. Tapi saat ditemukan, Soekartono sedang… mengasah keris.
Cerita ini nyaris seperti dongeng, tapi benar adanya. Seorang pemuda Jawa, yang pikirannya melampaui zamannya, duduk tenang mengasah warisan budaya leluhurnya saat dunia barat sedang bergantung pada kecerdasan otaknya.
Bayangkan itu.
Sayangnya, sejarah kita punya kebiasaan buruk: yang simbolik sering lebih diingat daripada yang substansial. Kartini—dengan segala kekuatan simboliknya—dirayakan setiap tahun. Tapi Soekartono? Namanya nyaris tidak muncul di buku pelajaran, apalagi di lomba poster Hari Kartini.
Padahal menurut sastrawan dan pemikir Radhar Panca Dahana, Soekartono adalah “otak brilian yang melebihi Soekarno dan Tan Malaka.” Radhar pernah berkata, kalau saja bangsa ini lebih serius membaca sejarah, mungkin kita akan melihat bahwa perlawanan tak selalu lewat pidato dan senjata. Kadang-kadang, lewat tulisan, lewat terjemahan, lewat kerja intelektual yang sunyi tapi tajam seperti keris yang diasah pelan-pelan.
Dua Saudara, Dua Jalan Sunyi
Kartini menulis surat, Soekartono menulis gagasan. Kartini berjuang membuka sekolah perempuan, Soekartono mendirikan lembaga kemanusiaan, menjadi ahli bahasa, penerjemah, dan jembatan pemahaman antara Timur dan Barat. Dua saudara ini, masing-masing mengambil jalannya. Tapi keduanya sama: memilih berpikir di zaman yang melarang orang berpikir.
Dan kita? Masih punya pekerjaan rumah yang panjang.
Masih banyak anak perempuan yang putus sekolah. Masih banyak perempuan yang suaranya dipotong di rapat-rapat penting. Masih banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan perempuan sebagai pengambil keputusan.
Mungkin kita tidak perlu menunggu 21 April untuk mengenang Kartini dan Soekartono. Karena mereka bukan tanggal. Mereka adalah semangat untuk terus berpikir, bertanya, dan melawan ketidakadilan, sekecil apapun bentuknya.
Dan kalau suatu hari kamu melihat seseorang yang sedang mengasah keris di sudut sepi rumahnya, jangan buru-buru menganggapnya kuno. Bisa jadi, ia sedang menyiapkan senjata paling tajam: kesadaran.
( Red )