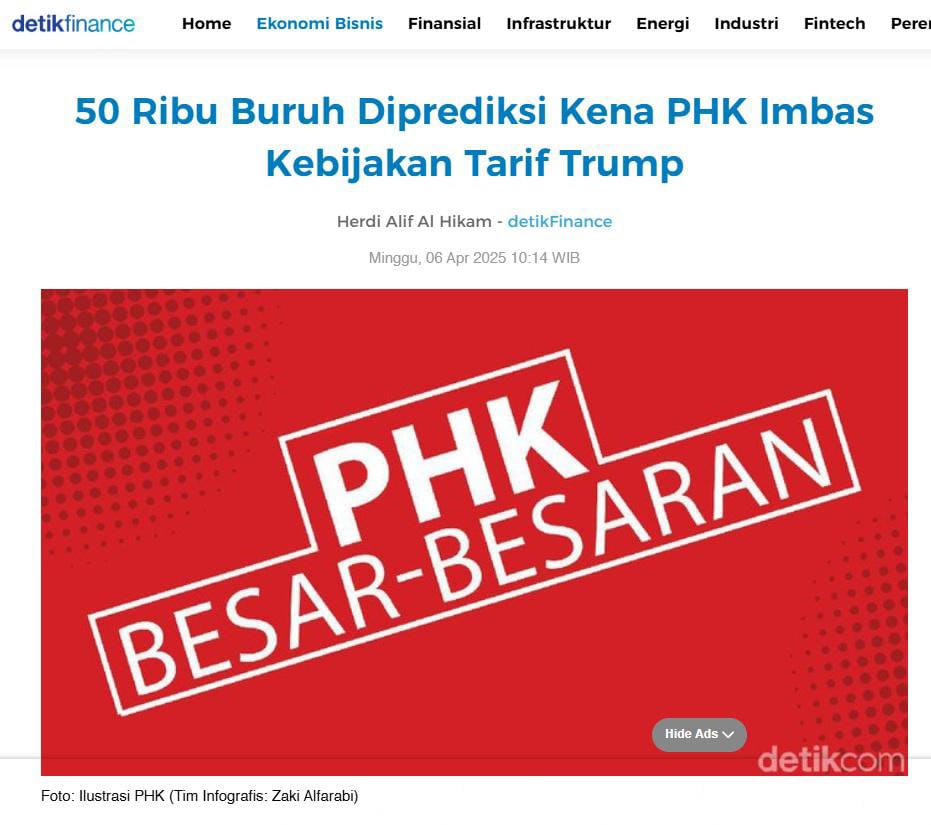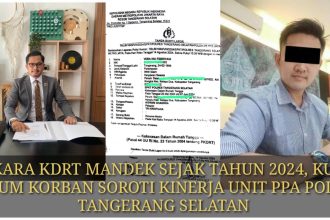Habis libur, harapan pegawai untuk kembali bekerja dengan tenang justru disambut kabar yang jauh dari menyenangkan. Pemerintahan Trump memutuskan memberlakukan tarif impor baru, kebijakan yang pasti akan mengguncang perekonomian global, termasuk Indonesia.
Masalahnya, hingga kini belum terdengar langkah antisipatif yang jelas dari pemerintah kita. Tidak ada penjelasan rinci, tidak ada peta jalan kebijakan untuk meredam dampaknya. Pegawai dan pelaku industri dibiarkan menerka-nerka sendiri, seolah-olah nasib mereka adalah urusan pribadi, bukan lagi urusan negara.
Padahal, sinyal bahaya sudah tampak jelas di depan mata. Sepanjang Januari hingga Februari 2025 saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya 18 ribu orang kehilangan pekerjaan. Ini baru data dua bulan, sebelum efek lanjutan dari perang dagang benar-benar terasa sepenuhnya.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah gelombang PHK ini akan semakin membesar dengan diberlakukannya tarif impor dari Trump? Kita belum tahu pasti seberapa dalam luka yang akan ditimbulkan, tapi satu hal jelas — badai besar bisa saja datang jika pemerintah terus abai dan terlambat membaca situasi.
Tanpa perlindungan yang memadai, industri dalam negeri bisa goyah. Beban biaya produksi akan naik, daya saing produk melemah, dan pada akhirnya, perusahaan-perusahaan yang tak kuat bertahan akan mengambil jalan pintas: memangkas tenaga kerja. Lagi-lagi, rakyat yang jadi korban.
Lebih memprihatinkan lagi, di tengah situasi genting ini, komunikasi dari pemerintah kepada publik terasa sangat minim. Seolah-olah mereka lupa bahwa di luar gedung-gedung mewah tempat mereka berkantor, jutaan rakyat sedang cemas menunggu kepastian. Bukankah seharusnya negara hadir untuk memberi penjelasan yang sederhana dan bisa dipahami semua kalangan?
Bandingkan dengan Singapura, yang sejak awal potensi gejolak ekonomi global, langsung merespons dengan keterbukaan. Menteri Perdagangan dan Industri mereka, Gan Kim Yong, bahkan dalam wawancara publik beberapa hari lalu, menjelaskan dampak dari kebijakan proteksionisme negara-negara besar secara gamblang. Pemerintah Singapura bukan hanya menjelaskan potensi dampak, tetapi juga menyampaikan strategi mitigasi mereka secara transparan: diversifikasi pasar ekspor, memperkuat sektor domestik, serta memberikan dukungan langsung bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Lebih jauh lagi, mereka mempermudah akses informasi dengan membuat portal khusus yang diperbarui secara berkala, menyederhanakan istilah ekonomi kompleks agar dipahami oleh publik, dan yang terpenting: menjaga moral masyarakat agar tidak panik, tapi waspada dengan langkah yang terarah.
Tak hanya Singapura. Malaysia pun tak tinggal diam. Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri mereka rutin menggelar forum diskusi publik untuk menjelaskan dampak konflik dagang dan menampung kekhawatiran para pengusaha lokal. Mereka bahkan melibatkan sektor swasta dalam perumusan kebijakan darurat, menyadari betul bahwa stabilitas ekonomi nasional adalah urusan bersama, bukan semata urusan pemerintah.
Sementara itu di Indonesia, komunikasi strategis seperti itu terasa nyaris tak terdengar. Kalaupun ada, bahasanya berputar-putar, lebih sibuk meredam kekhawatiran politik dibanding menjelaskan realitas ekonomi di lapangan.
Masyarakat jadi seperti berada dalam kabut tebal, dipaksa menunggu sambil bertanya-tanya: apakah pemerintah benar-benar memahami kegentingan ini? Ataukah mereka justru memilih bersikap seolah badai ini hanyalah angin sepoi-sepoi yang akan berlalu sendiri?
Jika terus begini, kita semua tahu, sejarah akan mencatat: bukan perang dagang yang mengguncang perekonomian kita, melainkan ketidakmampuan pemerintah membaca arah angin dan memandu rakyatnya keluar dari badai.